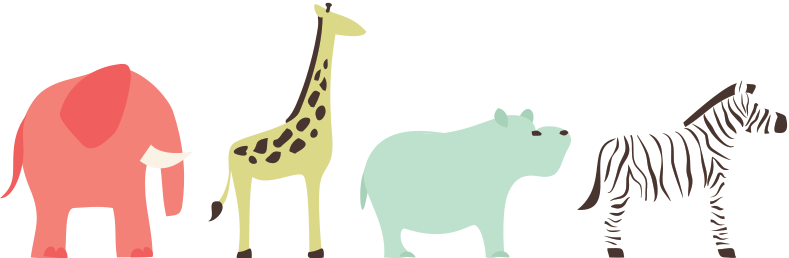Peluh masih belum hilang saat aku sudah harus bergegas melanjutkan aktivitas kembali. Bertemu dengan mahasiswa lagi. Menghadapi wajah-wajah yang tak kalah lelahnya denganku. Tapi aku sadar, bahwa aku punya tanggung jawab lebih pada mereka, yang sebenarnya mereka tak jauh berbeda denganku. Karena hampir dipastikan mereka pagi sampai sore bekerja, malamnya harus ke kampus.
Sore baru saja beranjak senja. Alunan suara kakaek tua membacakan ayat-atat suci terdengar dari pengeras suara masjid seberang gedung. Hari ini pertemuan terakhir dengan dua kelas yang aku ajar. Enam bulan ternyata sangat memberi kesan yang mendalam padaku terhadap mahasiswa yang aku ajarkan. Dapat menatap wajah-wajah mereka saat langkahku terhenti di depan kelas cukup membuatku kembali mengumpukan energi lagi agar aku bisa maksimal dalam mengajar. Karena, ada masa ketika aku merasa sangat lelah, apalagi ketika mahasiswa regular pagi mulai berulah dan membuat emosi meningkat.
“Malam, pak…”
Aku menoleh ke arah suara. Samar aku bisa mengenali suara itu. Tak terlalu asing. Dan tak berapa lama sosok yang tadi memanggilku mendekat. Dan dugaanku tak meleset.
Matanya bulat. Bulu matanya lentik. Dan tak bisa dibohongi adalah lesung pipitya yang begitu manis. Aku sebenarnya telah menaruh kagum padanya. Dari segi fisik biasa. Tapi itu nomor sekian bagiku. Karena aku hanya ingin melihat dirinya pada ‘kecantikan’ yang lain.
Namanya Miya. Dengan tas punggung dan selalu mengenakan celana jin ia mengayuh sepeda gunungnya dari rumahnya di bilangan Depok menuju kampus. Tiap hari. Tiap sore. Seperti sore ini, di penghujung semester di hari terakhir pertemuan dengan mata kuliah sosiologi sastra yang aku ajar. Keringatnya nampak bercahaya dari pantulan lampu jalan. Ia turun dari kursi sepedanya lalu menuntun menyejajarkan langkahku. Napasnya turun naik. Helm sepeda yang menutupi jilbabnya dilepaskan. Aku bisa membayangkan betapa ia begitu kelelahan mengayuh sepeda sejauh itu. Terlebih dia perempuan.
“Kamu luar biasa ya, Mi. pulang pergi naik sepeda ke kampus. Apa betis kamu gak berubah jadi talas tiap hari kayukh sepeda?”
Seperti biasa, ia menyunggingkan senyum khasnya. Aku selalu suka senyumnya. Lesung pipitnya. Aku alihkan mataku kearah lain sesaat setelah ia merasa ditatap lama olehku. Aku gugup.
“Selain sehat, ya minimal saya bisa menjalankan program go green, Pak. Lagipula bapak lihat sendiri kan, tubuh saya agak gemuk. Dengan saya naik sepeda bisa sekalian alih-alih diet alami. Hehehe”
Aku tertawa renyah. Yang membuat ia terlihat menggemaskan karena ia bertubuh sedikit gemuk. Meskipun sudah tertutup pakaian panjang dan memakai jilbab, tak bisa menutupi tubuhnya yang memang sejak enam bulan lalu aku mengenalnya.
Sesampainya di depan kelas, Pak Darman, bapak beranak tiga itu sudah duduk di kursi depan. Usianya melampaiu belasan tahun dariku, tapi semangatnya luar biasa. Mengejar S1 sebagai syarat sertifikasi guru menjadi alasan terbesarnya melanjutkan pendidikannya yang dulu hanya sampai SMA. Ia persis sekali dengan sosok almarhum ayah. Pembawaannya tenang dan begitu homoris.
Satu persatu mahasiswa kelas malam yang berjumlah hampir tiga puluhan mulai berdatangan. Rasanya, berat harus berpisah dengan mereka. Aku meraa dekat dengan mereka karena mereka tidak menganggapku sebagai dosen yang kaku. Aku juga dikenal humoris meski kadang dibilang jayus atau lebay. Tapi paling tidak, aku merasa diterima ditengah-tengah mereka.
“Apa kabar bapak-bapak dan ibu-ibu pada hari ini? Meski lelah saya yakin semangat kalian tak jauh berbeda dengan kelas regular pagi. Ini pertemuan terakhir untuk matakuliah yang bapak ajarkan. Bapak akan berikan kisi-kisi untuk kalian. Dengan harapan nilai-nilai uas kalian nati jauh lebih tinggi ketimbang nilai uts yang lalu.”
Aku tatap keseluruh sudut ruang. Kulihat si lesung pipit sedang merapikan jilbabnya. Ah, sungguh susah mengalihkan penglihataku kepadanya.
Ruangan terasa kaku. Entah kenapa selera humorku tiba-tiba menguap. Aku tak bisa membohongi perasaanku sendiri. Seharusnya aku sudah terbiasa menghadapi pertemuan terakhir dengan mahasiswa di akhir semester. Tapi ada yang membuatku berat. Ya, matanya. Mata yang tiba-tiba membuatku mengubah malas menjadi bersemangat, mengganti lapar menjadi kenyang dan dahaga menjadi telaga. Aku takut tak bisa melihatnya lagi jika berganti semester. Dan belum tentu aku akan mengajar dan bertemu dengannya lagi di semester depan.
“Bapak dan ibu sekalian, semoga yang telah bapak bisa ajarkan kepada kalian di mata kuliah ini bisa benar-benar bermanfaat bagi kalian. Bapak sadar masih banyak kekuarangan dalam mengajari kalian.”
Suasana hening. Tiba-tiba senyap seketika. Aku tak melihat Vika yang sedang bercermin seperti kebiasaan dia tiap mata kuliahku ataupun gerombolan Adi cs yang selalu eksis dengan hp di tangan. Mereka berlima memang kompak pake hp smart yang membuat mereka begitu khusyuk menatap layar hp masing-masing. Malam ini berubah.
Tok tok tok.
“Maaf pak, saya datang telat.”
Dita menatap mataku dengan tatapan bersalah. Aku sudah mengenal kebiasaannya datang terlambat. Ia bekerja sebagai staff di sebuah perusahaan kontraktor. Ia pernah memberi alasan mengapa ia selalu datang telat:
“Bos saya turun dari lapangan jam enam, pak. Belum lagi kalau tiba-tiba harus membuat laporan mendadak dari bos yang harus saya kerjakan segera. Yang lebih parah saya harus menunggu kereta lagi untuk mencapai ke kampus. Lima menit terlambat saja datang ke stasiun, saya harus mengojek. Yang parahnya, saya harus tebal muka melihat teman kantor yang tidak suka melihat saya pulang cepat. Karena mereka biasa pulang jam delapan malam.”
Aku persilakan duduk. Kali ini ia tak perlu memberikan alasan apapun. Lagipula sudah tak ada materi yang akan aku sampaikan di pertemuan terakhir malam ini.
“Pak,” Wagi, sang ketua kelas mengacungkan tangan. “Saya perwakilan dari teman-teman juga mengucapkan terima kasih atas kesedian bapak mengajari kami. Kami juga sadar banyak sekali perilaku kami yang membuat bapak kesal. Kami sungguh minta maaf, pak. Bapak sudah sangat baik kepada kami. Terima kasih, pak. Terima kasih.”
Aku tersenyum. Terharu. Tak banyak aku temui kelas yang membuatku merasa kehilangan. Persisnya sejak aku melihat sosoknya. Saat ia hampir menabrakku dengan sepedanya saat aku hendak menyeberang jalan di depan kampus persis dua pekan sebelum aku mengajar di kelasnya.
“Bapak juga minta maaf kalau bapak sering bergurau pada kalian. mungkin ilmu yang bapak berikan tak sebanding dengan yang kalian harapkan. Semoga ada sedikit yang nempel ya…”
Mereka menyengir kuda. Selanjutnya mulai mengalir kesan mereka selama mengikuti matakuliah sosiologi sastra. Secara keseluruhan komentar mereka positif. Meskipun tetap ada yang bilang kalau aku suka ngelucu tapi gak lucu. Aku terima semua dengan lapang dada. Aku juga memberikan kesan tentang kelas yang aku ajar ini.
“Kalian kompak. Ketika diminta membuat tugas pribadi atau kelompok kalian sigap. Meskipun ya masih banyak kekurangan. Tapi antusias kalian yang membuat saya sering merasa terharu. Kalian banyak yang bekerja di pagi hari, tetapi tentang tugas kalian tidak ketinggalan.”
Kelas sontak ramai. Berseru kegirangan.
“Iya doong paak…”
“Kelas kita kan kelas kompaak.”
“Kita gak mau kalah dengan kelas reguler pagi lah paaak…”
“Siapa duuuluu dosennyaaa…”
Dan yang membuat aku terkejut, Miya ikut berkomentar.
“Bapak kan dosen idola kita, jadi kita selalu sigap mengerjakan tugas-tugas. Hehehe.”
Rasanya aku mau terbang dia mengatakan itu. Meskipun ia menggunakan kata kita, tetapi ketika diucapkan olehnya, seolah ia yang mengatakan spesial untukku.
Tok tok tok.
Aku menengok ke arah pintu kelas. Yuwan, si botak yang usianya sepantar denganku masuk dengan napas tersegal-segal. Kerjanya jadi fotografer lepas. Aku sempat melihat-lihat hasil jepretannya. Apalagi ketika ia memperlihatkan hasil jepretannya tentang suku baduy. Aku sudah melihat jiwa sosialnya yang tinggi. Beberapa kali ia juga memotret anak-anak punk jalanan di daerah Depok yang sedang mengamen di angkutan umum.
“Maaf pak. Saya telat.” Katanya sambil mengatur napas. Aku melirik jam tanganku. Sepuluh menit lagi jam berakhir. Sebearnya dia termasuk mahasiswa yang jarang telat. Kalaupun telat ia biasanya izin lewat sms ataupun telepon.
“Ya silakan duduk.” Kataku dengan pura-pura kesal.
Biasanya aku melarang mahasiswa masuk kelas di setengah jam terakhir. Jika ada mahasiswa yang tetap mau masuk, konsekuensinya ia tetap dianggap tidak masuk. Berbeda jika dari awal sudah ada konfirmasi terlebih dahulu kalau datang telat. Tapi malam ini pertemuan terakhir, tak tega melihatnya memelas seperti itu.
Ini menit-menit terakhir. Aku membuka selembar kertas yang telah aku persiapkan. Malam ini aku ingin menghadiahi mahasiswaku dengan membacakan sebuah puisi, kalau bisa disebut puisi. Aku meminta semua tenang ketika aku bilang aku akan mebacakan puisi. Mendadak kelas sepi.
Aku menarik napas.
Beginilah caraku sosialisasi denganmu…
Huuuu… sontak kelas kembali gaduh. Mereka selalu ingat kata sosialisasi yang selalu aku dengungkan setiap pertemuan. Aku tak meminta untuk kembali tenang. Dalam hitungan detik kelas kembali sepi.
Ketika kau melihat matamu, aku sadar, aku sedang bersosialisasi denganmu.
Ketika tanpa sengaja mata kita bertemu, ku tahu, begitulah caramu sosialisasi padaku…
Saat aku mencoba membuka dialog ringan disela diskusi kelas ini, aku sadar, aku sedang bersosialisasi denganmu.
Ketika kau tertawa riang akan homor kecilku, ku tahu, begitulah caramu sosialisasi padaku…
Dan dipenghujung malam dipertemuan terakhir ini, saat air mataku jatuh karena akan kehilangan senyum manis dan tawa renyahmu, kau hadir memberi kisah pada jalinan sosialisasi diantara kita…
Akankah sosialisasi kita bermuara pada cinta? Entahlah…
“Baiklah, mungin hadiah puisi ini bisa menjadi kenangan di penghujung pertemuan kita ini.” kataku menutup sesi pembacaan puisi.
Suasana sedikit rusuh. Bisik-bisik tentang isi dari puisi yang bau aku bacakan. Beruntung tak ada yang menanyakan perihal tentang siapa yang ada di puisi yang aku buat.
“Sebentar pak, kami ada sesuatu untuk bapak.” Seru Asmi, mahasiswa bermata sipit yang berdiri di dua meja dihadapanku. Ia maju dan membawa sebuah kado.
Aku terkejut. Aku memerhatikan apa yang dipegangnya. Bentuknya tidak terlalu besar. Aku bisa melihat dari bentuknya sepertinya berisi beberapa buku bacaan.
“Ini kenang-keanngan dari kami, pak. Semoga bapak suka.” Katanya sambil menyerahkan kado dan menyalami tanganku.
Tiba-tiba ada haru yang menggelayuti hatiku. Mataku tiba-tiba basah. Ah, aku begitu sensitif untuk hal yang seperti ini. aku sempat menatap Miya, Kapan lagi aku bisa melihatmu sembilan puluh menit dalam seminggu sekali?
“Saya juga mau memberikan ini untuk bapak.” Yuwan bangkit dari duduknya. Ia menenteng bingkai foto.
“Semoga bapak berkenan menerima.” Katanya sambil menyodorkan bingkai berukuran sedang.
Mataku kembali berkaca. Aku tak meragukan keahliannya dalam meotret. Tapi aku juga tak pernah membayangkan akan di foto olehnya. Dan jujur, aku merasa tak pernah diminta atau meminta di foto. Apalagi dengan beberapa gambar ketika aku mengajar.
“Kamu diam-diam mengambil foto saya yaa…?” kataku sok marah. Mencoba mencairkan suasana.
Aku melihat mata-mata mahasiswa dihadapanku. Mereka sama sepertiku, diliputi rasa haru. Beebrapa mahasiswi bahkan mengusap air mata yang tanpa sadar mengalir di pipi.
“Terima kasih bapak dan ibu sekalian. Kado terindah bagi bapak adalah kalian, bertemu dengan kalian, mejadi bagian dari kisah kalian. semoga saya tidak hanya dikenang hanya dalam mata, tetapi juga pada hati-hati bapak dan ibu sekalian. Teerima kasih, terima kasih…”
Aku memeluk Yuwan dan menyalami Asmi. Sedetik kemudian satu persatu mahasiswa dihapanku bangkit menghampiriku. Dan aku kembali menatap Miya, matanya. Pasti akan selalu ku rindu…
16.44 WIB
Selasa, 19 Juni 2012